Setiap kota pasti menorehkan kesan tersendiri bagi penghuninya, lepas dari apakah dia penghuni tetap ataupun sekadar singgah karena tuntutan sekolah atau pekerjaan. Kalau dibalik, setiap orang pasti menyimpan kesan tersendiri tentang kota yang ditinggalinya baik itu hanya untuk sementara ataupun dalam jangka waktu yang sangat lama.
Haryoto Kunto (1940-1999) menuangkan kesan-kesannya tentang Kota Bandung dalam banyak buku, dua di antaranya sudah menjadi legenda dalam dunia perbukuan seputar sejarah Bandung, yakni Wajah Bandoeng Tempo Doeloe (Granesia, 1984) dan “Semerbak Bunga di Bandung Raya (Granesia, 1986).
Haryoto Kunto memang bukan yang pertama menulis buku “sejarah” Kota Bandung, sebelumnya sudah ada 2 jilid buku berbahasa Sunda, “Bandung Baheula” karangan Moech. Affandi (Guna Utama, 1969), dan “Keur Kuring di Bandung” karangan Sjarif Amin (…). Dalam bahasa Belanda juga banyak buku yang khusus membahas Kota Bandung seperti “Bandoeng” karangan H. Buitenweg (Katwijk, Holland, 1976) atau “Gids van Bandoeng en Omstreken” karangan S.A. Reitsma dan W.H. Hoogland (Vorkink, Bandoeng, 1921). Di dalam bahasa Inggris ada “Bandung & Beyond” karangan Richard & Sheila Bennet (Aneka Karya, Bandung, 1980).
Daftar di atas hanya secuil saja dari banyak buku lain yang sudah membicarakan Kota Bandung sebelum Haryoto Kunto menerbitkan buku-bukunya. Yang cukup menarik perhatian dan menjadi pembeda buku-buku karangan Haryoto Kunto adalah keluasan bahasan dan penggunaan bahasa yang sangat longgar, nyaris seperti bahasa lisan yang digunakan sehari-hari. Mungkin faktor bahasa ini pula yang membuat buku-buku Haryoto Kunto menjadi begitu populer dan dikenang oleh banyak orang.
Dalam salah satu bagian tulisannya, Haryoto Kunto menulis: “Wah, bila Cuma berbenah diri kalau ada penggede pusat yang datang meninjau, benar-benar brengsek dong.” Kalimat ini dilanjutkan dengan kutipan “”Emang, Kota Bandung sih Brenk-sex!” kata si Dolly yang sering mangkal di Kebon Raja, nimbrung bicara.” Ya, begitulah gaya Haryoto Kunto menulis atau berbicara, nyaris ceplas-ceplos. Dalam menyimak ceritanya pembaca bahkan tak pernah dipusingkan dengan apakah tokoh Dolly yang disebutkannya itu benar-benar ada atau hanya rekaannya saja dalam mengemas cerita. Di banyak bagian tulisan, Haryoto Kunto cukup banyak menggunakan dialog (entah karangan atau bukan) dalam menyampaikan ceritanya. Sepertinya saat menulis itu Haryoto Kunto mengandaikan dirinya sedang bercerita secara lisan kepada para pendengarnya.
Faktor lain yang membedakan buku-buku Haryoto Kunto dengan buku lainnya yang membahas Kota Bandung, disampaikannya lewat judul buku yang digunakan, “Wajah Bandoeng Tempo Doeloe”. Dengan sumber referensi begitu banyak buku antik yang berhasil dikumpulkan di rumah tinggalnya di Jl. H. Mesrie No. 5, Haryoto Kunto mereka-reka seperti apa rupa Kota Bandung di masa lalu. Dari buku-buku lama digalinya informasi sebanyak mungkin, lalu disusun sedemikian rupa sehingga mendapatkan gambaran umum rupa Kota Bandung dari waktu ke waktu.
Yang berikut ini khusus tentang buku Wajah Bandung Tempo Doeloe. Saya tak ingat berapa kali buku ini keluar masuk koleksi bukuku, aktivitas jual-beli buku bekas membuat banyak koleksi bukuku bisa keluar masuk dengan agak leluasa. Sejak diterbitkan pertama kali oleh Penerbit Granesia tahun 1984, buku yang legendaris ini ternyata tidak mengalami banyak cetak ulang. Sampai tahun 2014, baru 5 kali cetak ulang, semua oleh penerbit yang sama. Dapat dibandingkan dengan banyak buku best-seller masa kini yang dalam satu tahun saja bisa cetak ulang sampai belasan kali.
Kebetulan buku yang sedang saya pegang ini merupakan cetakan yang kelima. Seingat saya, dua cetakan terakhir (2008 & 2014) buku ini dicetak dengan ukuran yang lebih besar (24 x 18 cm) dibanding sebelumnya (22 x 15 cm), selain itu sampulnya dibuat hard-cover. Perbedaan lainnya, dua buku edisi terakhir memiliki gambar sampul yang berbeda dan menggunakan bahan kertas berwarna kuning pucat yang belakangan ini memang banyak dipakai untuk penerbitan buku.
Pada bagian isi, ada penambahan pengantar dari Walikota Bandung, Ridwan Kamil, dan Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan. Di penerbitan awal, pengantar hanya diberikan oleh Walikota Bandung, Ateng Wahyudi. Pada bab terakhir yang merupakan kumpulan foto perbandingan antara foto zaman baheula dengan foto terkini juga mengalami perubahan, tidak lagi memuat foto-foto tahun 1984 seperti dalam terbitan pertamanya, melainkan foto-foto yang diambil tahun 2007. Saya tidak menemukan keterangan kenapa buku terbitan 2014 ini menggunakan foto-foto pembandingnya dari tahun 2007 dan bukan 2013 atau 2014. Saya juga tidak berhasil menemukan siapa nama fotografer untuk foto-foto “baru” ini.
Isi buku Wajah Bandoeng Tempo Doeloe dibagi ke dalam 18 Bab, dimulai dengan Bab I ”Pendahuluan” lalu Bab II “Negorij Bandong”, yang sebagian ceritanya sudah saya kutipkan di atas, yaitu latar belakang kelahiran Kota Bandung. Selanjutnya adalah bab-bab yang tidak terlalu ketat dengan urutan waktu namun secara umum ada gambaran kronologis. Bab-bab awal diisi oleh nostalgia Kota Bandung, cerita-cerita tempo dulu atau di sini sering disebut “zaman normal”, uraian pernik sejarah yang dianggap ikut membangun kejayaan Kota Bandung. Bab XIV memasuki “Wajah Pudar Bandoeng Tempo Doeloe” yang dilanjutkan dengan Bab XV “Pemugaran Bangunan Bersejarah”, kemudian kembali ke nostalgia dengan pilihan tema yang agak spesifik pada Bab XVII “Seabad Jalan Braga”. Rangkaian ini ditutup oleh Bab XVIII dengan judul “Bandung Antara Harapan dan Kenyataan”.
Haryoto Kunto membuka cerita dari mention pertama nama Bandong oleh Juliaen de Silva pada tahun 1641: “Aan een negrije genaemt Bandong, bestaende uijt 25 a 30 huijsen. (Ada sebuah negeri bernama Bandong yang terdiri dari 25-30 rumah)”. Lalu pencarian sulfur untuk campuran bubuk mesiu oleh Abraham van Riebeek yang sampai mendaki Gunung Papandayan dan Tangkubanparahu, berlanjut ke cerita tentang orang kulit putih pertama yang menjadi warga Tatar Bandung, yaitu Kopral Arie Top, yang mendapatkan tugas dari Kompeni (1741) sebagai Plaatselijk Militair Commandant (Komandan Militer Menetap di Satu Daerah). Sebagian besar Tatar Bandung saat itu masih berupa hutan dan rawa-rawa dengan beberapa kampung kecil di beberapa tempat.
Setelah itu cerita bersambung ke kedatangan Gubernur Jenderal Hindia Belanda H.W. Daendels yang membangun Jalan Raya Pos (Grote Postweg) membentang dari Anyer di Jawa Barat sampai Panarukan di Jawa Timur. Pembangunan jalan raya ini mengakibatkan ibukota Kabupaten Bandung harus dipindahkan dari Krapyak, Citeureup (Dayeuhkolot sekarang) ke lokasi Alun-alun Bandung sekarang. Tanggal dikeluarkannya surat keputusan resmi perpindahan ibukota ini dijadikan sebagai patokan kelahiran Kota Bandung, yaitu 25 September 1810. Dapat dibayangkan saat itu pembangunan fasilitas pemerintahan yang baru dipusatkan di sekitar Alun-alun: Pendopo, masjid, paseban, kompleks kapatihan, pasar, banceuy, dan pesanggrahan. Disebutkan saat itu sudah ada sejumlah kampung tua di Tatar Bandung, seperti Cikalintu, Balubur, dan Cikapundung Kolot.
Perpindahan ibukota kabupaten diikuti dengan perpindahan pusat pemerintahan Karesidenan Priangan dari Cianjur ke Bandung pada tahun 1864. Artinya ada perkembangan situasi kota Bandung mengikuti perpindahan ini, jalur-jalur jalan baru dibuat, dan orang-orang baru berdatangan. Groneman mencatat pada tahun 1870-an banyak orang sibuk membuka lahan di kota untuk dijadikan kebun dan bermukim di situ. Haryoto Kunto mencatat paling sedikit lahir sekitar 20 nama kampung dengan kata kebon di depannya, seperti Kebon Kawung, Kebon Jati, Kebon Kalapa, Kebon Jeruk, dst.
Masuknya jalur kereta api ke Bandung tahun 1884 menambah semarak kota kecil ini, disusul pembangunan berskala besar oleh Bupati RAA Martanagara yang bertindak sebagai Mandor Besar memimpin para kuli pribumi. Beberapa karya Martanagara adalah:
- Lahan kota Bandung bagian selatan yang kebanyakan masih berupa rawa dijadikan persawahan, kolam ikan, atau disaeur (ditimbun tanah) seperti bisa dilihat dari nama tempat Situ Saeur.
- Menggali dan memperbaiki saluran air (kanal) seperi Cikapayang dan Cikakak.
- Penggantian atap dan tembok rumah menggunakan bata dan genteng yang dibuat di Merdika Lio.
- Pembangunan jembatan-jembatan, termasuk penggantian bahan jembatan yang tadinya barbahan kayu dan bambu menjadi batu, tembok, dan besi.
- Menata kawasan Grote Postweg sekitar Alun-alun menjadi kawasan perkantoran (Eropa) dan Braga menjadi kawasan pertokoan.
Pada Bab XII dengan judul “Bandung Penuh Sanjung”, Haryoto Kunto menceritakan bagaimana sejumlah orang Indo atau Belanda yang sudah kembali ke negerinya memendam kerinduan yang mendalam kepada kota ini. Cerita ini dilanjutkan dengan membahas berbagai julukan yang pernah disematkan kepada Kota Bandung, seperti Paradijs op Aarde, Paradise in Exile, sampai Bandung Kota Intelektual. Cerita berlanjut ke sekolah-sekolah tempo dulu, kehidupan kesenian, kelahiran Bandoengsche Radio Vereeniging (BRV), lalu beranjak sampai cerita soal kamp interniran di Bandung.
Bab XIII dengan judul Bandung adalah Bandung diisi oleh perbandingan perkembangan kota di Jakarta. Haryoto Kunto menyoroti pembangunan kota yang mengarah Jakarta-sentris. Tulis Haryoto Kunto: “Adalah usaha yang sia-sia, melawan dan membendung arus modernisasi dan kemajuan yang melanda masyarakat, maupun kota-kota besar di Indonesia. Namun kita harus cukup selektif dalam memilih bentuk teknologi yang akan diterapkan dalam planning dan pembangunan kota. Sebagai contoh: apakah tepat pengoperasian bis kota dengan ukuran long chassis dan mempunyai berat melebihi kekuatan jalan di Bandung yang sempit dan penuh tanjakan?”
Hampir di setiap bab yang ditulisnya Haryoto Kunto menyelipkan catatan dan pertanyaan tentang arah pembangunan dan perubahan kota yang dinilainya tidak memiliki kesadaran sejarah, sehingga Kota Bandung mengalami kerugian sejarah-budaya kota yang besar. Banyak harta karun sejarah-budaya yang musnah begitu saja. Pada bagian akhir Bab XIV Haryoto Kunto juga mempertanyakan soal penggantian nama-nama jalan dengan nama baru yang ternyata tidak menunjukkan identitas atau kaitan erat dengan sejarah yang terjadi di Kota Bandung.
Haryoto Kunto seperti hendak terus menegaskan betapa cantiknya Kota Bandung tempo dulu, betapa rinci perancangannya, dan betapa nyaman suasananya. Sayang semua itu hanya cerita tempo dulu. Perkembangan yang terjadi, terutama setelah masa kemerdekaan, justru berlawanan dengan keadaannya dulu. Kecantikan dan kenyamanan itu pelan-pelan memudar akibat pembangunan yang tidak terkendali dan kesadaran sejarah para penghuni kota yang dirasa sangat kurang.
Satu hal yang khas dari buku-buku karya Haryoto Kunto adalah kehadiran kutipan-kutipan di setiap pembukaan bab. Begitu juga dengan buku Wajah Bandoeng Tempo Doeloe, penggalan puisi, lirik lagu, atau pepatah, menghiasi di sana-sini. Bila karya masterpiece-nya, “Semerbak Bunga di Bandung Raya” (Granesia, 1986), dibuka dengan cuplikan dari naskah Kropak 632 Kabuyutan Ciburuy: hana nguni hana mangke, tan hana nguni tan hana mangke…, maka buku Wajah Bandoeng Tempo Doeloe dibuka dengan cuplikan dari “Wawacan Purnama Alam” karya R. Soeriadiredja: Beunang nungtik ti leuleutik, nyutat-nyatet ti bubudak, tataros ti kolot kahot, juru dongeng alam kuna, ayeuna ditukilna, disurup kana lagu, ditulad dijieun babad. (Diteliti sejak kecil mula, dicatat sejak kanak-kanak, bertanya kepada orang tua, tukang cerita dulu kala, sekarang diungkapkan, digubah jadi lagu, direka jadi cerita).
Kiranya kutipan terakhir ini cukup menjelaskan proses berkarya Sang Kuncen Bandung, Haryoto Kunto, bahwa bukan hanya catatan dan tulisan yang dikumpulkannya, melainkan juga cerita-cerita, obrolan, lagu, dan semua sudah dilakukannya (secara konsisten) sejak kecil.
***
Tulisan ini dibuat untuk keperluan Kelas Resensi di Komunitas Aleut, sebuah kegiatan mingguan baru yang diadakan di Perpustakaan Kedai Preanger

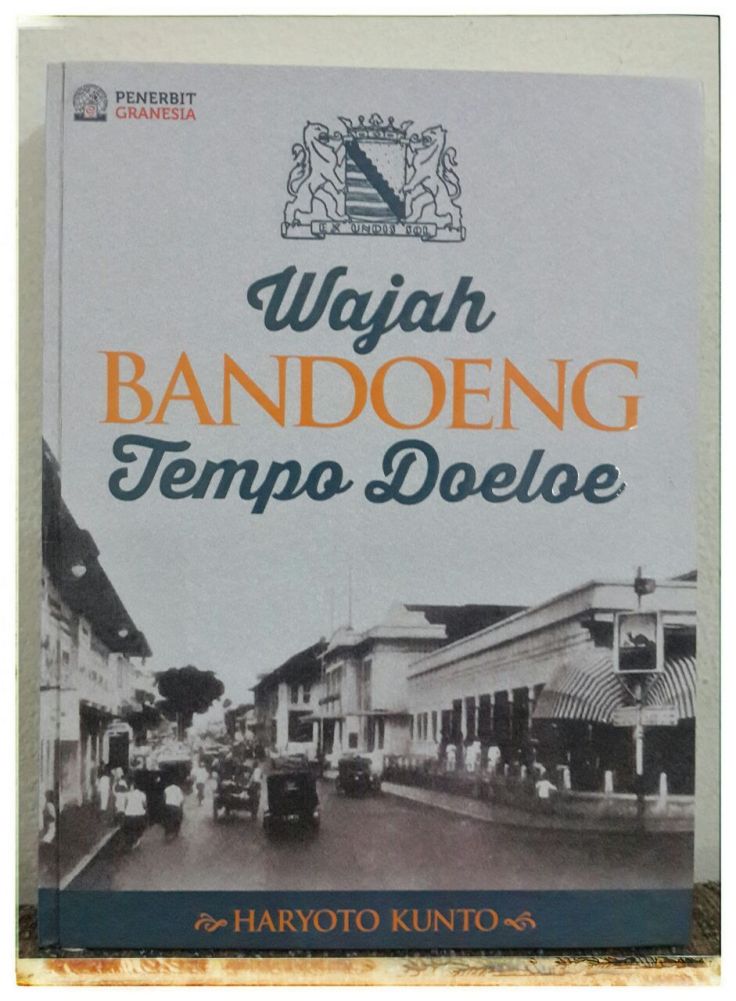

Leave a comment